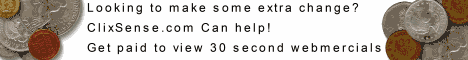Oka Ishak, menggela napas panjang. Laki-laki asal Medan, Sumatera Utara itu seperti membuang beban berat yang selama ini menyesakkan dadanya. “Kita berterimakasih dengan adanya saluran air Ladong-Lamreh ini, tapi bagaimana pun kesadaran masyarakat adalah kunci dari semua persoalan yang membuat saluran ini terus mengucurkan air,” kata Oka Ishak dalam sebuah wawancara.
Oka Ishak adalah Sekretaris Alue Pochik. Sebuah kelompok pemanfaat air di Kecamatan Masjid Raya bentukan Plan Aceh. Kehadiran Alue Pochik di kecamatan pesisir pantai timur Kebupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam ini memang bukan basa-basi. Kelompok yang dalam bahasa Aceh berarti saluran air ini terbentuk karena saluran pipa Ladong-Lamreh sering terganggu.
Tidak hanya itu, Plan Aceh menganggap masyarakat delapan desa, mulai Desa Ladong, Desa Ruyung, Desa Berandeh, Desa Meunasah Kulam, Meunasah Mon, Meunasah Keude dan Desa Lamreh tidak punya “rasa memiliki” atau sense of belonging pada proyek pipa Ladong-Lamreh dan pernak-perniknya. Masih adanya pelubangan ilegal pipa saluran Ladong-Lamreh, rusaknya kran air di hidran umum sampai penggunaan air bersih yang boros dan bukan untuk minum adalah bukti semua gejala tidak adanya sense of belonging.
Karenanya, perlu ada upaya taktis untuk memunculkan sense of belonging. Dengan difasilitasi oleh Plan Aceh, dibuatlah sebuah pertemuan berkala antara masyarakat dan pejabat kecamatan untuk berbicara menyangkut upaya penyerahan pipanisasi Ladong-Lamreh. Seluruh pemimpin desa, mulai Kepala Dusun, Kepala Lorong, Imam Geucik, Geucik, Kepala Mukim dan seluruh pejabat kecamatan diundang untuk itu. Singkat kata, masyarakat sepakat dengan ide pembentukan kelompok pemanfatan air yang disebut Alue Pochik.
Untuk menjaga sistem kerja Alue Pochik, dipilih pengurus yang merupakan tokoh-tokoh yang disegani oleh masyarakat Desa Ladong hingga Desa Lamreh. Sa’ban Siregar warga Krueng Raya dipilih sebagai Ketua, Oka Ishak warga Desa Ladong dipilih sebagai sekretaris dan Erni warga Krueng Raya terpilih sebagai Bendahara. Di atas pengurus, ada dewan pembina yang berisi semua pejabat teras di tingkat desa dan kecamatan. Diharapkan Alue Pochik mampu menjadi solusi tidak lancarnya saluran air Ladong-Lamreh. “Alue Pochik memang dibentuk agar ada jaminan air tetap mengalir, persoalan sementara teratasi,” kata Djuneidi Saripurnawan, Research and Development Coordinator Plan International Aceh.
Meski begitu, Plan Aceh menyadari, peran Alue Pochik belum sepenuhnya maksimal. Buktinya, sejak kelompok itu dibentuk pada awal tahun 2007, sampai sekarang tetap air di pipa Ladong-Lamreh tidak bisa mengalir utuh. Bahkan dibalik itu, Plan Aceh menyimpan kekhawatiran, Alue Pochik akan tergoda untuk mengkomersialisasikan air yang seharusnya bisa dinikmati secara gratis.
“Isu komersialisasi air kan sedang marak dibicarakan, bisa-bisa Plan Aceh akan tersandung persoalan ini karena kita yang memfaslitasi terbentuknya Alue Pochik,” kata Djuneidi. Kekhawatiran Plan Aceh memang bukan pendapat pribadi. Hingga saat ini, masih ada penduduk di delapan desa itu yang berpikir Alue Pochik tidak bekerja efektif.
Senada dengan Plan Aceh, Sekretaris Alue Pochik Oka Ishak pun memiliki pemikiran yang tidak jauh berbeda. Menurut Oka, sampai saat ini masih ada sebagian masyarakat yang saling menyalahkan karena alir tidak lancar mengalir. Masyarakat Desa Ladong menyalahkan Krueng Raya (Meunasah Kulam, Meunasah Mon, Meunasah Keude dan Lamreh) karena dinilai mengurangi jatah mereka, sementara masyarakat Krueng Raya menyalahkan Ladong, karena dinilai menutup saluran.
“Meski begitu, Alue Pochik memilih untuk mendengarkan semua aspirasi itu sembari terus memberikan penjelasan,” kata Oka. Selain itu, Alue Pochik juga melakukan kerja-kerja nyata, seperti penutupan pada pelubangan ilegal. Meski diakui oleh Oka, hal itu belum sepenuhnya membawa hasil. “Kita akan melihat dulu, apakah ada kebocoran lagi. Sampai saat ini, air masih berhenti di perbatasan Krueng Raya,” jelasnya.
Hasil kerja lain Alue Pochik yang bisa dinikmati masyarakat adalah pembuatan sistem “iuran” untuk masyarakat yang memanfaatkan air. Iuran ini digunakan untuk mengisi khas desa perbaikan sumber air bukit Ladong dan membayar Ismail, penjaga mata air. Setiap keluarga diwajibkan membayar Rp.3000,-. Memang, belum semua warga desa Ladong sampai Desa Lamreh bersedia membayar. Dengan alasan ketidaklancaran air.
Alue Pochik juga memiliki agenda jangka panjang yang pelan-pelan sudah mulai dikerjakan. Yakni meteranisasi untuk seluruh keluarga yang tinggal di delapan desa yang dilewati pipa Ladong-Lamreh. Sebagian rumah sudah mendapatkan meteran, namun mayoritas masih belum tersentuh program itu. “Kami sudah memohon ke American Red Cross untuk memberikan akses ke rumah-rumah. Itu baru usulan dan belum realisasi,” kata Oka.
Program lain adalah membuka salah satu hidran umum (HU) sebagai satu-satunya tempat legal untuk mendapatkan air bagi penjual air yang menggunakan becak motor. HU yang akan dibuka untuk umum itu terletak di depan Masjid Ladong. Setiap becak motor yang mengambil air diwajibkan untuk membayar infak ke masjid. Uang infak ini akan digunakan untuk pembiayaan Masjid Ladong yang saat ini masih dalam proses pembangunan.
Karena benyak dan rumitnya pekerjaan, Alue Pochik meminta masyarakat untuk bersabar dan memberi waktu mereka untuk bekerja. “Banyak sekali kerjaan kita, yang terbaru saja adalah persoalan tidak lancarnya air karena banyak angin yang ikut terbawa oleh air, angin itu membuat air kadang keluar, kadang tidak,” kata Oka. Sepertinya pekerjaan rumah Alue Pochik tetap akan bertumpuk-tumpuk.