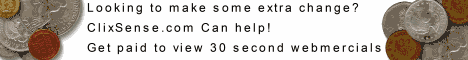Sebuah aliran Islam di Jombang, Jawa Timur bersikukuh menggunakan cara hitung kuno atau aboge, untuk menentukan awal pelaksanaan puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Hasilnya, Hari Raya Idul Fitri pun digelar lebih lambat dari perayaan yang dilakukan oleh mayoritas umat Muslim di Indonesia, Minggu (14/10) “Ini persoalan syariat (cara) yang kami yakini benar, dan kami siap mati untuk itu,” kata KH. Nasuha Anwar, pemimpin aliran Tarekat Nashabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah al Aliyah pada The Jakarta Post.
Sebuah aliran Islam di Jombang, Jawa Timur bersikukuh menggunakan cara hitung kuno atau aboge, untuk menentukan awal pelaksanaan puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Hasilnya, Hari Raya Idul Fitri pun digelar lebih lambat dari perayaan yang dilakukan oleh mayoritas umat Muslim di Indonesia, Minggu (14/10) “Ini persoalan syariat (cara) yang kami yakini benar, dan kami siap mati untuk itu,” kata KH. Nasuha Anwar, pemimpin aliran Tarekat Nashabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah al Aliyah pada The Jakarta Post.Sekilas, tidak ada yang berbeda dengan Masjid Baitul Mutaqin di Dusun Kapas, Dukuh Klopo, Jombang, Jawa Timur. Namun, masjid yang dibangun tahun 1898 di ujung kota Jombang itu adalah pusat ajaran tarekat Nashabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah al Aliyah. Sebuah aliran tarekat Islam yang memiliki pola peribadahan yang lebih menekankan pada sholat dan wirid. Penganut tarekat ini meyakini, cara yang dilakukannya mampu memperpendek jalan ke surga.
Tarekat yang akrab disebut Nashabandiyah Khalidiyah ini juga meyakini telah menggunakan cara-cara beribadah RasulullahMuhammad SAW dengan utuh. Cara-cara itu yang selama ini sudah mulai ditinggalkan oleh umat Islam kebanyakan dan menggantinya dengan pendekatan teknologi. Yang paling khas adalah penggunaan cara hitung kuno (aboge) untuk menentukan awal Ramadhan dan Idul Fitri.
Selama ini umat Islam kebanyakan hanya menggunakan cara rukyatul hilal atau melihat bulan secara langsung (biasa dipakai Nahdlatul Ulama/NU)dan hisab atau menghitung secara matematis pergantian bulan (biasa dipakai Muhammadyah). “Tapi cara aboge ini lebih bisa menentukan dengan pas seperti yang diajarkan mursyid (panutan) kami Syech Abdullah Fakir,” kata Nasuha Anwar.
Selain itu, Nashabandiyah Khalidiyah juga memiliki ritual (amaliyah) yang dilakukan di tempat khusus atau Kholwat. Ritual yang biasanya dilakukan pada Bulan Jawa Selo (Jumadil Akhir) itu digelar di kholwat-kholwat yang terletak di samping masjid Baitul Mutaqin. Sembari melakukan puasa tiga hari berturut-turut dan menyepi. “Bentuk amaliyah, termasuk apa yang wirid yang dibaca kali satu ini hanya khusus diberitahukan kepada anggota Nashabandiyah Khalidiyah,” katanya.
Keunikan Nashabandiyah Khalidiyah pertama kali diperkenalkan oleh Syech Abdullah Fakir, menantu Syech Usman Ja’fani, salah satu pembawa Islam di Tanah Jawa. Syech Abdullah Fakir yang lulusan Mekkah itu mendapatkan ilmunya dari Jabal Kubais Mekkah. Ajaran itu kemudian diturunkan kepada Kyai Ja’far, yang diturunkan lagi ke Kyai Anwar, ayah dari Kyai Nasuha Anwar.
“Ajaran Kyai Anwar yang utama adalah Kholwat selama 40 hari di bulan Selo, yang intinya mengimani ketauhidan, tata krama dalam beribadah dan penghormatan kepada orang tua,” kaya Kyai Nasuha. Saat ini, kata kyai yang memiliki dua istri dan enam anak itu, jumlah anggota Nashabandiyah Khalidiyah mencapai 3000-an orang yang tersebar di Jawa dan Sumatera. Namun, seluruh kegiatan dipusatkan di Masjid Baitul Mutaqin yang terletak di tanah wakaf seluas 800 meter persegi itu. Di tanah wakaf itu terbaring jasad Syach Abdullah Fakir dan keturunnannya.
Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Kebontemu Jombang, Salikun, mengatakan, meski Nashabandiyah Khalidiyah memiliki perbedaan dengan syariat yang dipercaya mayoritas NU, namun hal itu tidak membuat Nashabandiyah Khalidiyah dimusuhi. “Masyakat NU di Jombang tidak merasa terganggu dengan keberadaan Nashabandiyah Khalidiyah, kami tetap hidup berdampingan dengan damai,” kata Salikun.
Selama ini, kata Salikun, bila ada warga Dusun Kapas yang tidak setuju dengan Nashabandiyah Khalidiyah, mereka biasanya memilih untuk beribadah di masjid lain yang tidak menganut aliran Nashabandiyah Khalidiyah. “Kita sama-sama Islam, meskipun nasab (silsilah keturunan) dan syariat (cara) yang kami anut berbeda,” katanya. Islam sebagai agama Rahmatanlil ’Alamin terealisasi di kawasan ini.